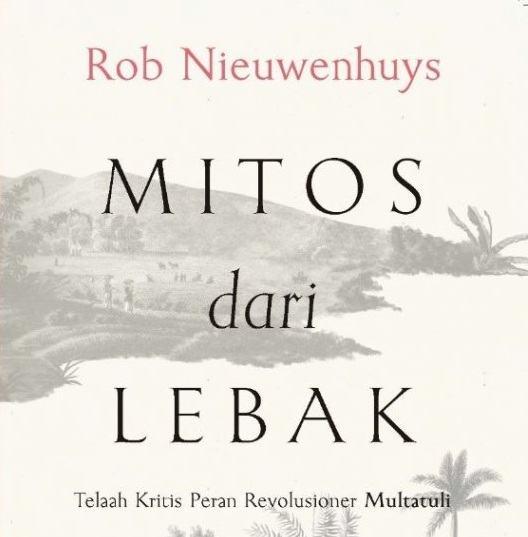
Demitologisasi Multatuli
Pada tahun 1975, Rob Nieuwenhuys menulis tiga esai panjang dalam majalah opini berbahasa Belanda, Haagse Post, bertepatan dengan perayaan seratus tahun meninggalnya Multatuli. Ketiga tulisan itu memuat data-data yang berbeda pada umumnya, terkait novel Max Havelaar sebagai karya sastra di satu sisi, dan Multatuli sebagai penulis sekaligus tokoh yang selama ini didengung-dengungkan sebagai penentang kolonialisme. Menariknya, esai yang ditulis oleh Rob itu, justru bukan untuk melegitimasi sikap Multatuli sebagaimana ia tuangkan dalam novelnya yang kesohor, “Max Havelaar of de Koffij-velingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij”, yang terbit pertama kalinya dalam bahasa Belanda tahun 1860.
Rob Niuwenhuys berusaha membongkar mitos-mitos yang sejauh ini berkembang, baik di kalangan intelektual maupun di kalangan para sastrawan yang menganggap bahwa Multatulimemihak kaum pribumi yang terindikasi adanya penindasan dan perampasan yang dilakukan oleh Bupati Lebak, Banten. Sikap ini tentu saja mendapat pujian dan perhatian. Apalagi ia seorang Belanda yang membela kepentingan kaum pribumi dengan membumihanguskan sistem yang memeras keringat rakyat melalui novel yang ditulisnya. Karena terbitnya Max Havelaar, konon, kebijakan sistem tanam paksa yang telah terjadi semasa Multatuli menjabat sebagai asisten residen Lebak ini, berganti haluan dan membuka gerbang sistem politik etis pada permulaan abad ke-20.
Laiknya seorang pahlawan yang diagung-agungkan, sampai saat ini Multatuli bukan hanya sekadar nama yang menempel dalam buku-buku sejarah. Ia menjadi sebuah angan-angan yang tumbuh di masyarakat, menjadi ikon perlawanan atas kebobrokan sistem. Namanya dijadikan sebuah jalan, nama museum, juga dijadikan nama perpustakaan atau nama taman bacaan di pelosok-pelosok desa. Hal ini tiada lain karena ia, Multatuli, seorang yang menderita, berhasil menciptakan perlawanan agung atas kesewenang-wenangan penguasa lewat novelnya, Max Havelaar. Bahkan, Pramoedya Ananta Toer menyebut Max Havelaar sebagai “buku yang menghancurkan kolonialisme”.
Sementara Rob Nieuwenhuys berkata lain. Melalui catatannya yang berjudul, Mitos dari Lebak: Telaah Kritis Peran Revolusioner Multatuli,semua kisah-kisah heroik yang disandarkan pada Multatuli, berbalik arah, dan menjadi sosok yang cenderung “bermasalah”. Rob Niewenhuys dalam esai-esainya yang telah dihimpun ini, mencoba untuk mendobrak kekeliruan yang selama ini terlampaui menjadi mitos, dengan disertai data dan fakta yang berbeda pada umumnya. “Multatuli tidak menulis sebuah laporan mengenai kejadian di Lebak itu, bukan pula sebuah brosur ataupun pamflet, melainkan benar-benar sebuah roman, yaitu dalam arti kata suatu produk yang didasarkan pada angan-angan”, tulisnya.
Tiga tahun sebelum buku Max Havelaar terbit, Gubernur Jendral Duymaer van Twist mengumumkan untuk memindahkan Multatuli berdasarkan surat resmi. Kejadian ini bermula saat Multatuli mengajukan pengaduan kepada atasannya, C.P. Bres van Kempen, lantaran telah terjadi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati di wilayah pemerintahannya di Lebak yang mengacu pada arsip-arsip hasil pemeriksaan. Masalah ini langsung mendapat sorotan dari para pejabat kolonial, sampai mereka meminta agar Multatuli diberhentikan dari jabatannya sebagai asisten residen Lebak.
Dalam Mitos dari Lebak: Telaah Kritis Peran Revolusioner Multatuli,sesungguhnya, Rob mengaburkan analisisnya. Apakah ia menyoroti sosok Multatuli sebagai mitos, ataukah catatan kritisnya ini ditujukan pada mitos Max Havelaar sebagai karya yang berpengaruh dalam wacana sastra dan politik? Persoalan ini pada akhirnya akan dijumpai oleh para pembaca. Karena Rob mencampurbaurkan kritiknya pada Multatuli dan Max Havelaar secara bersamaan. Namun, terlepas dari hal tersebut, buku ini berhasil menampilkan demitologisasi terhadap ikon Multatuli yang selama ini dianggap sebagai tokoh perlawanan.***
(Hafidz Azhar/Pembaca Sastra dan Sejarah)
Comments (0)