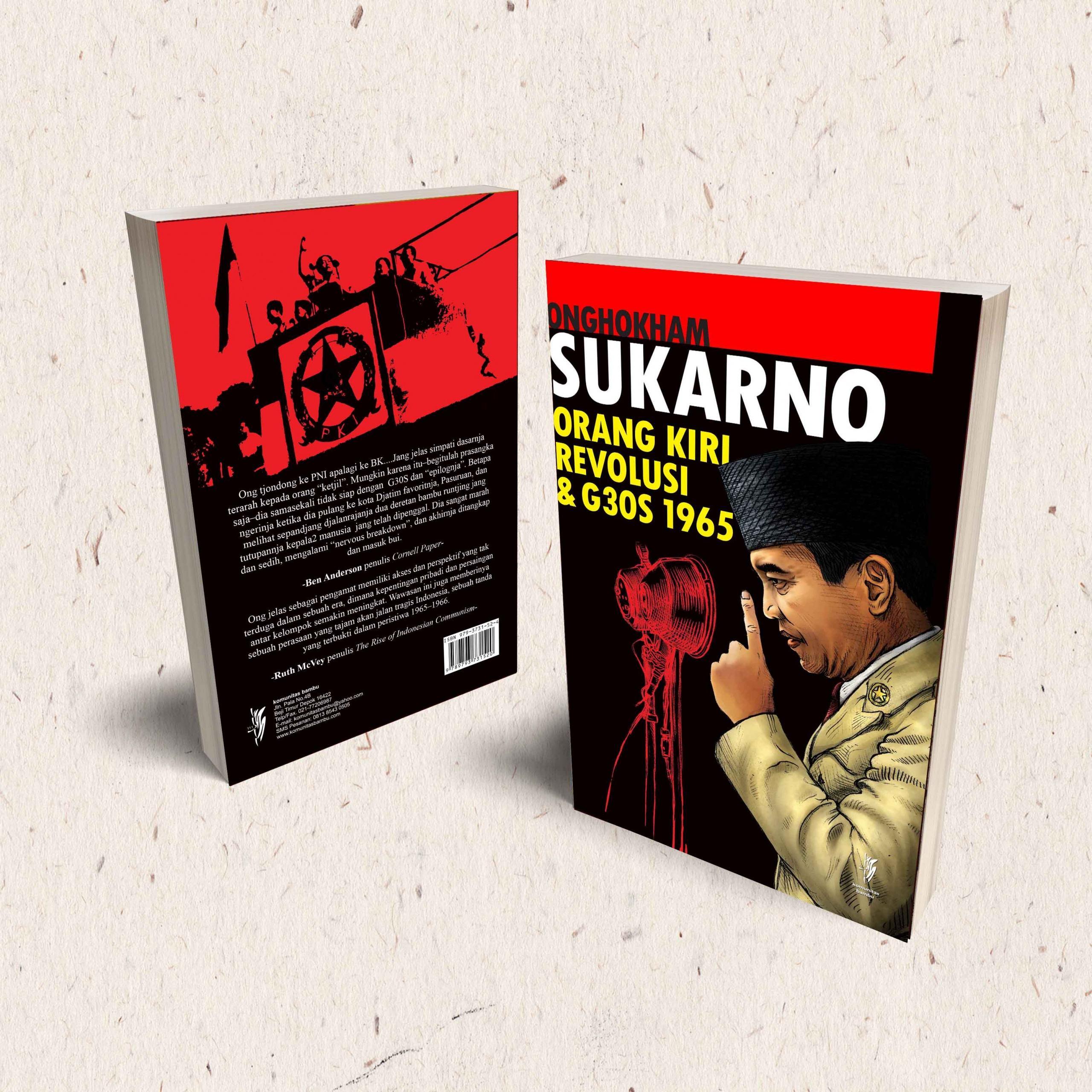
Onghokham Menimbang Bung Karno
Peter Kasenda,
Sejarawan dan Pengajar di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta
Ada kekaguman yang diekspresikan sejarawan Onghokham kepada Sukarno. Namun,
kekaguman itu tidak membuat dirinya luput melihat ironi Sukarno: yang menjadi
korban dari konsistensinya sendiri.
Sumbangan Onghokham, biasa disapa Ong, yang terpenting adalah ia telah
menampilkan dirinya sebagai cendekiawan publik. Dialah sejarawan yang paling sering
menulis di media. Melalui tulisannya, Ong bergelut seraya mengajak kita melihat
persoalan masa kini untuk dibandingkan dengan peristiwa pada masa lampau.
Perbandingan secara diakronis inilah yang menyebabkan sejarah di tangan Ong seolah-
olah hadir di pelupuk mata, hidup, inspiratif, dan menarik.
Namun, bagaimana kalau Ong menulis sejarah yang sezaman dengannya, dialaminya,
dan bahkan ia terlibat di dalamnya? Inilah yang menarik selama membaca Sukarno,
Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965 karya Ong, suatu bunga rampai yang berkaitan
dengan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi pada abad ke-20, periode kehidupan
penulis yang sezaman dengan sejarah yang dikisahkan.
Menurut Ong, banyak sejarawan segan menulis atau meneliti sejarah kontemporer atau
masa yang sezaman dengan masa hidup sejarawan itu. Bahkan, ada yang mengatakan
semakin kuno suatu zaman untuk diteliti, semakin ilmiah sifatnya karena emosi,
kepentingan, dan lain-lain sudah mereda, serta mungkin bahannya pun lebih lengkap.
Pendapat ini belum tentu benar. Sejarah kuno Indonesia, misalnya, sedikit sekali
bahannya. Pun emosi dan kepentingan tentang suatu zaman lampau masih kuat.
Korban konsistensi
Ketertarikan Ong pada figur bapak pendiri ini bisa ditelusuri dari persahabatannya
dengan aktivis-aktivis GMNI yang berdomisili di Asrama Daksinapati UI Rawamangun.
Terlebih lagi Onghokham mempunyai kecenderungan politik pada PNI yang
mempunyai hubungan emosional dan ideologis dengan Sukarno dan pada Sukarno
sendiri. Ong dan Sukarno dilahirkan di Provinsi Jawa Timur dan Ong mempunyai
kebanggaan yang berlebih atas provinsi kelahirannya.
Bagi seorang sejarawan, yang mengalami zaman Sukarno dan menulis mengenai
Sukarno, delapan tahun sesudah Sukarno tiada, tidaklah mudah. Periode Sukarno
mungkin terlalu dekat bagi sejarawan untuk melihat semua fakta. Kebesaran seorang
tokoh membuat dirinya terselimut dengan nilai-nilai dan anggapan yang telah
dikenakan kepadanya. Bagaimana bisa menulis biografi sesungguhnya untuk
mengetahui ”badan alamiah” orang tersebut jika terselubung realitas-realitas palsu,
yang menghambat pengenalan langsung terhadap si tokoh?
Sukarno adalah contoh yang jelas dari ironi sejarah dan penilaian sejarah. Sejak remaja
ia berjuang. Ia berhasil. Bukan saja dalam usaha bersama mencapai cita-cita
kemerdekaan, tetapi juga menjadi keberhasilan itu sendiri. Ia menjadi presiden dan
kemudian dianggap dan menganggap diri sebagai personifikasi segala nilai dan slogan
yang sedang dikembangkan. Namun, setelah kudeta 30 September 1965, ketika anak-
anak muda meneriakkan mengenai pentingnya pembubaran PKI, Sukarno tidak mau
membubarkan PKI. Sukarno tetap konsisten dengan pendirian mengenai perlunya tiga
kekuatan besar bersatu menghadapi imperialisme dan kapitalisme. Di sini, kata Ong,
Sukarno sendirian menghadapi realitas yang tak sesuai lagi dengan dirinya. Kejatuhan
Sukarno, menurut Ong, disebabkan korban pandangan politiknya sendiri yang
dipegangnya sejak 1926.
Pengalaman Trauma
Sebenarnya, Ong juga menjadi korban tidak langsung dari Peristiwa Gerakan 30
September. Tulisan Saya, Sejarah dan G30S 1965 di buku ini berbicara mengenai
pengalaman yang membuatnya trauma. Setelah G30S, Ong menyaksikan pembantaian
massal di Jawa Timur, tempatnya berasal. Kenyataan itu membuat dirinya marah dan
terguncang. Ketakutan menghampiri dirinya. Tanpa alasan jelas Ong ditahan penguasa
militer pada Januari 1966. Penahanan atas diri Ong tidak berlangsung lama. Atas
bantuan Nugroho Notosusanto, Ong bisa menghirup udara bebas. Barangkali itu adalah
periode paling kelam dalam hidup Ong.
Pada awal Orde Reformasi, Masyarakat Sejarawan Indonesia mengadakan seminar
Memandang Tragedi 1965 secara Jernih di Serpong, Tangerang. Melalui makalah
”Refleksi tentang Peristiwa G30S (Gestok) 1965 dan Akibat-akibatnya”, yang dimuat
kembali dalam bunga rampai ini, Ong berbicara mengenai latar belakang peristiwa
tersebut ketimbang epilog Peristiwa G30S. Di sini Ong menyatakan pembantaian
massal yang terjadi adalah perang saudara. Ini disebut perang saudara karena kalau
tentara saja yang melakukannya tidak mungkin kehancuran PKI demikian total
sehingga tidak ada bayang-bayangnya sama sekali kini.
Mengenai peristiwa kelabu tersebut, Sukarno memilih untuk memakai istilah Gestok
dan bukan istilah Gestapu yang populer itu, yang bagi kalangan berpendidikan
mempunyai makna sampingan yang jelas menunjuk pada organisasi teror Hitler, yaitu
Gestapo. Menurut Ong, istilah Gestok memang lebih tepat dari sudut sejarah,
sedangkan istilah Gestapu politis dan hina bagi gerakan tersebut. Namun, karena
pemenang perebutan kekuasaan menyebut peristiwa itu Gestapu (Gerakan September
Tiga Puluh), sejarawan sampai sekarang memakai istilah tersebut. Sejarah adalah
sejarah pemenang, bukan sejarah orang kalah.
Sebelum Peristiwa G30S, Sukarno merupakan satu-satunya pemimpin nasional yang
paling terkemuka selama dua dasawarsa lebih, yaitu sejak Sukarno bersama Hatta, pada
1945 mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia satu-satunya presiden negara-bangsa
baru itu. Dengan karisma, kefasihan lidah, dan patriotismenya yang menggelora, ia
tetap sangat populer di tengah semua kekacauan politik dan salah urus perekonomian
pascakemerdekaan. Bahkan, sampai 1965 kedudukannya sebagai presiden tak
tergoyahkan.
Namun, pasca-Peristiwa G30S situasinya menjadi lain. Menurut Ong, Angkatan 66
berhasil menurunkan Sukarno dan foto-foto Sukarno yang berada di setiap sudut jalan
di Jakarta. Anehnya, lebih dari 20 tahun kemudian, pemerintahan Orde Baru mulai
mengembalikan nama Sukarno-Hatta (yang mewakili generasi 28) ke proporsi
kebenaran sejarah. Ada Bandara Sukarno-Hatta, ada penghormatan sebagai pahlawan
nasional, dan lain-lain. Sukarno juga menjadi mitos yang bernilai politis dan
disejajarkan dengan cita-cita kebangsaan. Foto-foto Sukarno diarak peserta kampanye.
Sayangnya, Ong tidak menjelaskan bahwa pada saat itu terjadi struggle of power
sehingga sering secara sadar atau tidak sadar gerakan mahasiswa Angkatan 1966
menjadi alat. Angkatan ’66 memang monumental dalam hal mobilisasi mahasiswa,
tetapi gerakan mereka telah masuk ke dalam setting politik yang dibangun oleh militer.
Melalui bunga rampai ini, Ong ingin mengatakan bahwa Peristiwa G30S telah membuat
Pemimpin Besar Revolusi hilang dari panggung nasional dan internasional. Ternyata
revolusi tidak berjalan sebagaimana digariskan Sukarno. Selama pemerintahannya,
situasi sosial-politik telah tumbuh ke dalam suatu kondisi matang bagi terjadinya
revolusi lain. Sukarno digulingkan oleh kontrarevolusi yang dilancarkan Soeharto.
Dalam konteks ini, benar juga ungkapan bahwa setiap revolusi harus mengorbankan
anak-anaknya sendiri. Sukarno hanyalah salah satu bukti tambahan atas ungkapan ini.
Sumber: KOMPAS, Senin, 5 Oktober 2009
Comments (0)