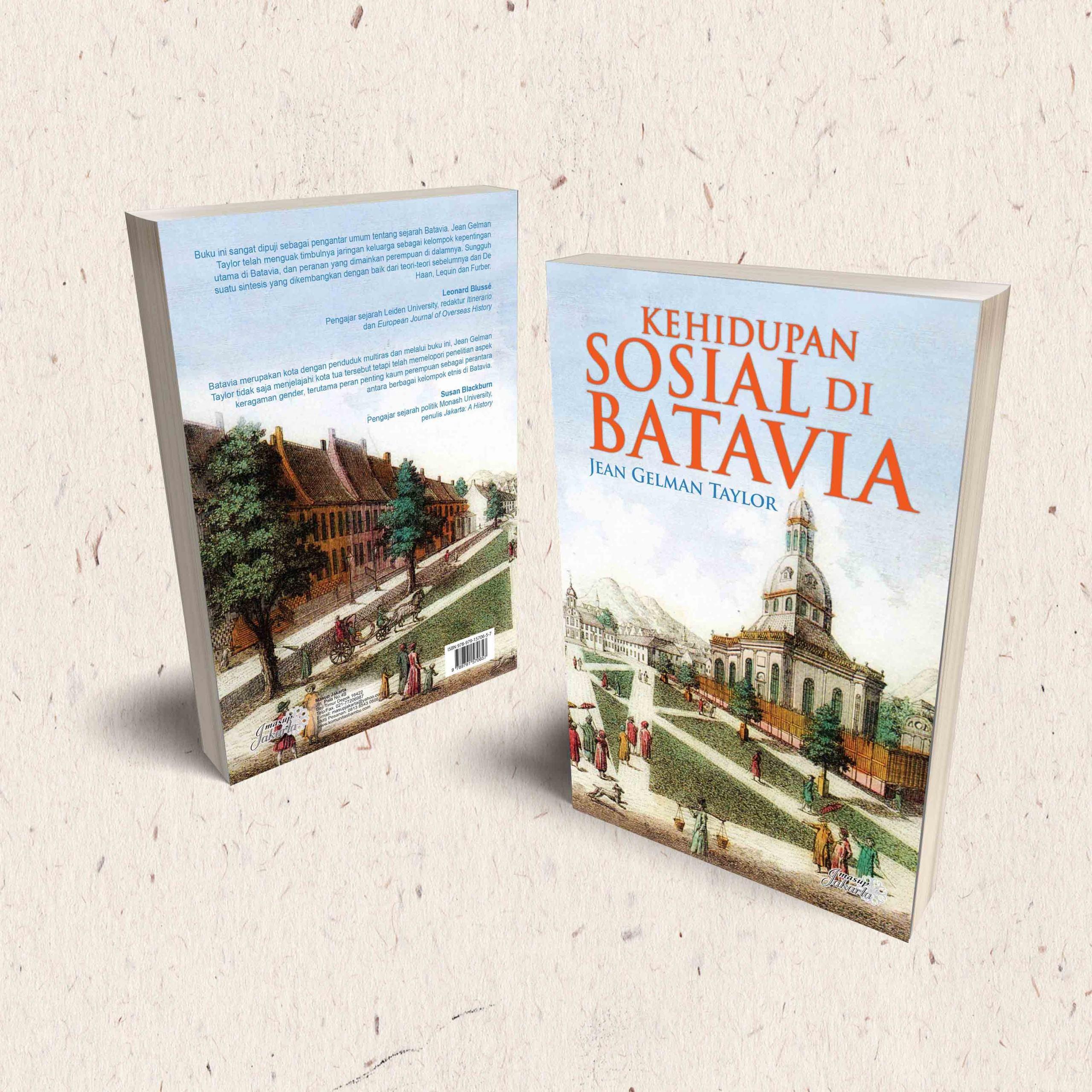
Kehidupan Sosial di Batavia
Grace Tjan
Kontributor goodreads.com
Orang ‘Belanda’, yang menjadi elite masyarakat kolonial selama berabad-abad di Indonesia, ternyata bukanlah suatu masyarakat yang monolitik. Seperti bangsa asing lainnya yang hidup di Nusantara, mereka juga mengalami proses adaptasi, kreolisasi dan bahkan asimilasi dengan masyarakat Indonesia. Hanya berselang beberapa puluh tahun saja sejak kota Batavia didirikan oleh Jan Pieterzoon Coen, telah terbentuk suatu masyarakat berciri Indisch, yang terdiri atas orang ‘Belanda’ yang lahir dan dibesarkan di Indonesia. Tak sedikit dari antara mereka yang beribu pribumi atau wanita Asia lainnya, umumnya para budak yang diimpor dari koloni-koloni Belanda lain di Asia Selatan. Hal ini terjadi karena kegagalan usaha Coen untuk mendatangkan wanita Belanda dari “keluarga baik-baik” ke Batavia dalam jumlah yang memadai untuk menjadi pasangan para pegawai VOC. Untuk menghindari akibat negatif dari praktek ‘pernyaian’, kebijakan VOC selanjutnya malah mempromosikan pernikahan legal di antara para pegawainya dan wanita Asia yang dibaptis, dengan tujuan agar terbentuk masyarakat Eurasia yang stabil sebagai pendukung koloni yang setia.
Dalam beberapa generasi saja telah muncul komunitas Mestizo berdarah campuran (tapi berstatus Eropa) yang kemudian menjadi elite penguasa VOC di Indonesia. Suatu hal yang menarik, bahwa banyak dari para Gubernur Jenderal yang memerintah pada abad ke 17 dan 18 lahir atau dibesarkan di Indonesia sebagai anggota komunitas ini. Walaupun kebijakan VOC mendiskriminasi orang Kreol dan Eurasia, namun dengan berbagai cara, termasuk melalui pernikahan strategis, mereka berhasil mencapai puncak kekuasaan kolonial. Hal yang menarik lainnya ialah bahwa masyarakat ini bersifat matrilineal, di mana status sosial dan kekayaan berpindah melalui garis perempuan. Ini juga merupakan efek dari kebijakan anti nepotisme VOC yang membuat anak laki-laki dari masyarakat ini dikirim ke Belanda untuk berkarier di sana, sedangkan anak perempuan dipertahankan di Indonesia untuk nantinya menjadi istri pejabat VOC yang karirnya cemerlang.
Pengaruh yang kuat dari pihak perempuan yang berdarah Asia membuat masyarakat Mestizo ini banyak mengadopsi gaya hidup Indonesia, mulai dari kebiasaan mengenakan kebaya, makan sirih, memelihara budak, mandi dua kali sehari, sampai dengan kegemaran bertelanjang kaki dan duduk di tikar. Serangan terhadap gaya hidup yang terlalu ‘pribumi’ ini beberapa kali dilakukan oleh elite VOC. Sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa dan tatakrama Belanda yang baik dan benar didirikan untuk mendidik anak-anak mereka, namun usaha-usaha ini tidak mengalami kemajuan yang berarti.
Kejayaan kaum Meztizo berlangsung sampai kebangkrutan VOC pada tahun 1799. Gubernur Jenderal berikutnya, Daendels, adalah orang Belanda totok yang langsung dikirim dari Eropa. Demikian juga dengan Raffles, yang berkuasa pada masa Peralihan Pemerintahan Inggris. Raffles mendirikan berbagai institusi seperti koran berbahasa Inggris dan Belanda, klub sosial dan teater untuk ‘mengeropakan’ mereka. Kebaya dianggap sebagai baju dalam yang tidak sopan dan para perempuan didorong untuk mengikuti teladan Olivia, Nyonya Raffles, untuk mengenakan gaun Eropa. Tempolong ludah dibuang dari acara-acara resmi yang disponsori pemerintah untuk menghilangkan kebiasaan menyirih yang “menjijikkan”. Namun seperti usaha-usaha sebelumnya, pemerintah Inggris juga tidak berhasil melakukan perubahan yang berarti. Menurut Taylor, hal ini disebabkan karena singkatnya masa pemerintahan Inggris, dan juga karena (ironisnya) orang Inggris yang datang ke Indonesia sendiri juga membawa kebudayan yang tidak murni Eropa (!). Seperti Belanda di Indonesia, mereka juga telah “terindiakan” sebagai efek dari ratusan tahun kolonisasi Inggris di India, seperti yang diantaranya diungkapkan dalam buku White Mughals: Love and Betrayal in Eighteenth-Century India.
Setelah kembalinya Belanda ke Indonesia, tekanan terhadap kelompok Mestizo bertambah kencang. Para Gubernur Jenderal dikirim langsung dari Belanda dan anggota keluarga Mestizo yang dahulu berpengaruh pada era VOC tidak lagi diterima dalam eselon atas pemerintahan kolonial. Mereka lalu menjadi pengusaha swasta. Kebudayaan Indisch juga mundur dari ruang publik dan hanya dipraktekkan dalam situasi domestik, terutama setelah makin banyak datang imigran Eropa pada abad ke 19 dan 20. Dan akhirnya, kebudayaan ini hilang setelah Indonesia merdeka, dan “hanya dapat hidup di dalam catatan-catatan yang sentimental dan menyentuh hati dari para penulis Tempoe Doeloe“.
Comments (0)