Abdullah Al-Misri
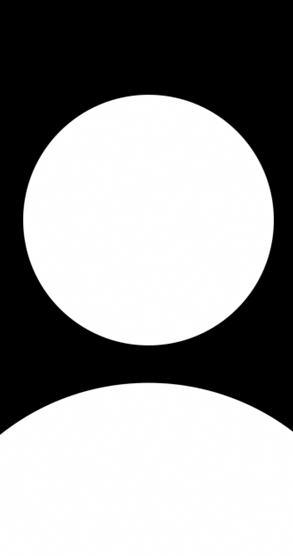
Penulis
Abdullah Al-Misri
Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan “zaman edan”. Masa itu, masa yang sangat halai-balai dalam sejarah pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah diambil alih oleh tiga bangsa berturut-turut, dan tiap gubernur baru merombak sistem jajahan, serta melancarkan politik pembaruan.
Berakhirnya kekuasaan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan peperangan yang terus berkecamuk di Eropa berakibat penting bagi Pulau Jawa. Ekonomi kolonial mengalami pasang surut, meski dalam beberapa bidang tampak kemajuan.
Suasana politik panas dan sungguh merepotkan; pemerintah kolonial gusar, sementara sebagian masyarat, yang antara lain kaum ulama, bersiap-siap “memberontak”. Selangkah demi selangkah menjurus ke perang besar (kelak kita kenal dengan nama Perang Jawa dan seorang pangeran bernama Diponegoro menjadi bintang).
Pada awal 1780-an, akibat perang Inggris-Belanda, Hindia Belanda menjadi terisolir, sehingga perdagangan terhenti dan Kompeni VOC yang sudah dirongrong oleh korupsi hampir bangkrut. Pada saat itulah orang Inggris menjejakkan kakinya di Pulau Pinang.
Seorang komisaris Belanda diutus ke Batavia untuk mengarsiteki reorganisasi pengelolaan Kompeni, ialah S.C. Nederburgh yang tiba di Jawa pada 1793. Namun, komisaris itu hanya memandang kepentingannya sendiri, sedangkan pada tahun itu juga, negeri Belanda menyatakan perang kepada Republik Prancis.
Dua tahun kemudian, Belanda dikuasai oleh angkatan revolusioner dan menjadi Bataafsche Republiek. Tahun berikutnya “ketujuh belas tuan” (Heeren XVII) dilepaskan dari jabatannya sebagai penguasa tertinggi Kompeni, dan sebuah panitia khusus mengambil keputusan agar kontrak Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda itu tidak diperpanjang setelah habis masanya pada 31 Desember 1799. Selanjutnya, Hindia Belanda akan menjadi jajahan langsung pemerintah Belanda.
Kala itu, Belanda bersekutu dengan Prancis melawan Inggris. Armada Inggris tidak menyerang Jawa, tetapi merampas Malaka, pantai barat Sumatra, serta Ambon dan Banda, dan menenggelamkan kapal-kapal Belanda di Laut Jawa. Walaupun begitu, dengan berakhirnya monopoli Belanda, pemerintahan Batavia dapat menjual hasil dagangannya, justru pada waktu harga rempah-rempah sedang menjulang tinggi, sehingga negara kolonial mengalami masa kemakmuran selama beberapa tahun.
Namun keadaan ini tidaklah berjalan stabil. Situasi di Eropa lekas merubah lagi keadaan di Hindia Belanda. Pada 1806, Republik Belanda dijadikan kerajaan dan adik Napoleon sendiri dinobatkan menjadi Raja Louis. Waktu itulah Daendels ditahbiskan sebagai Gubernur Jenderal Hindia. Daendels tiba di Jawa pada Januari 1808 dan memerintah selama tiga tahun sampai dengan Mei 1811. Waktu Raja Louis diturunkan dari takhta oleh Napoleon dan negeri Belanda disatukan dengan kekaisaran Prancis, maka Daendels diganti oleh J.W. Janssens. Saat itu pula orang Inggris merasa diri terancam oleh kekuasaan Prancis di Jawa, sehingga Lord Minto menyerang Batavia pada Agustus 1811 dan menaklukkan pasukan kolonial Prancis dalam waktu enam minggu.
Dus, mulailah masa pemerintahan Lieutenant-Governor Raffles yang kemudian berakhir dengan pengembalian kawasan jajahan Hindia kepada pemerintah Belanda pada Agustus 1816. Napoleon sudah jatuh, kerusuhan di Eropa mulai mereda, orang Belanda menata kembali pemerintahannya di Hindia, sedangkan Raffles mencari-cari sebuah pangkalan di daerah Selat Malaka, dan akhirnya mendirikan kota Singapura pada 1819.
Selama tiga tahun memerintah, Daendels menjalankan sebuah politik yang sangat otoriter demi perombakan keadaan militer, ekonomi, administrasi, dan hukum. Secara berturut-turut “Sang Mareskalek” (Maarschalk) menundukkan Sultan Banten, Sultan Cirebon, dan Sultan Yogyakarta.
Dia membentuk sebuah tentara dalam jumlah besar: 18.000 orang. Dia mengubah sistem peradilan. Sebuah jalan lintas Pulau Jawa (De Groote Postweg) dibukanya dari Anyer hingga ke Panarukan. Benteng Belanda di Batavia dirubuhkannya, dan kantor-kantor pemerintahan dipindahkannya ke Weltevreden. Untuk mengisi kas negara, kabupaten Besuki, Panarukan, dan Probolinggo dijualnya kepada Kapiten Tionghoa di Surabaya. Sebuah benteng (Ford Louis) dibangunnya di Teluk Surabaya.
Wawasan Politik Sastrawi
Zaman itulah yang menjadi kerangka dan latar belakang hidup Abdullah bin Muhammad al-Misri. Seperti jelas dari nisbahnya, dia seorang peranakan Mesir. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakr Raja Bandarkhan bin Syeikh Ibrahim al-Misri (Zaini-Lajoubert, 2008).
Menurut Henri Chambert-Loir dalam buku bunga rampainya Iskandar Zulkarnain, Dewa Mendu, Muhammad Bakir, dan Kawan-Kawan: Lima Belas Karangan Tentang Sastra Indonesia Lama (2014), Keluarga Abdullah menetap di Palembang sekitar pertengahan abad ke-18, mungkin datang dari Kedah: waktu menyadur naskah Hikayat Mareskalek pada 1831-1832, penyalinnya yaitu seorang Palembang bernama Kiai Rangga Satyanandita menamakan Abdullah seorang “peranakan Kedah”.
Pada pertengahan abad ke-18, orang Arab di Palembang masih sedikit. Pasca beberapa waktu di kota kelahirannya, Abdullah pindah, mungkin ke Batavia atau barangkali lebih dahulu ke Pontianak; di situ rupanya Abdullah bergaul dengan masyarakat Arab tersohor di lingkungan istana, pertama-tama dengan Sultan Syarif Qasim bin Abdurrahman al-Qadri, yaitu anak Sayyid Abdurrahman yang mendirikan kota Pontianak pada 1771. Syarif Qasim sendiri menjadi Sultan Pontianak dari 1808 s/d 1819.
Antara 1809 dan 1824, Abdullah menulis lima karangan, yang kelimanya termasuk golongan sejarah dan politik, yaitu Bayan al-Asma’ (1810), Hikayat Mareskalek (k.l. 1815),Arsy al-Muluk (1818), Hikayat Raja-Raja Siam (1823), dan Hikayat Tanah Bali (1824). Dengan nota bene judul kedua dan ketiga bukan judul asli, melainkan judul yang direka oleh editornya lama kemudian (Hikayat Mareskalek oleh van Hoevall atau de Hollander; Arsy al-Muluk oleh Zaini-Lajoubert).
Kelima karangan Abdullah itu dipersembahkan kepada berbagai kepala negara, sesuai dengan tradisi penulisan risalah adab dalam sastra Arab dan Parsi. Kedua yang pertama kepada dua sultan di Kalimantan (Kutai dan Pontianak), yang ketiga kepada seorang pembesar Petapahan (Riau), yang keempat kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, yang kelima kepada seorang Adipati yang tidak diketahui identitasnya.
Monique Zaini-Lajoubert dalam bukunya Karya Lengkap Abdullah bin Muhammad al-Misri (2008: 183-90), mengatakan bahwa dalam karyanya yang perdana (Bayan al-Asma’, 1809), Abdullah sebenarnya mendedahkan bahwa dia pernah berkunjung, atau barangkali menetap, di Kutai dan berkenalan dengan keluarga sultan. Episode ini kabur, bahkan mungkin tidak pernah terjadi, oleh karena nama pengarang Bayan al-Asma’ tertulis Abdullah bin Muhammad Bakri al-Misri (bukan Abu Bakr), sehingga tidak sepenuhnya pasti sama dengan Abdullah yang saya maksud dalam tulisan ini. Tambahan pula, karangan Bayan al-Asma’ itu sesuai dengan kecenderungan Abdullah menulis risalat peradaban, namun isinya bertentangan dengan paham-paham yang dikemukakan dalam pelbagai karangan Abdullah selanjutnya.
Abdullah pernah bermukim juga di Batavia dan menjadi murid saudara sepupunya sendiri, yaitu seorang syaikh yang terkenal bernama Abdurrahman bin Ahmad al-Misri. Abdurrahman itu pernah menjadi saudagar di Palembang dan di Padang, sebelum menetap di Petamburan, Batavia. Dalam karya Abdullah, kita dapat melihat bahwa pengaruh Syeikh Abdurrahman atas pandangan dan pemikirannya mungkin cukup besar. Barangkali dialah yang memupuk minat Abdullah terhadap ilmu politik, sehingga pada sekitar 1815, Abdullah menulis karangannya yang paling masyhur, yaitu Hikayat Mareskalek. Dalam lema pengantar hikayat itu, Abdullah menjelaskan niatnya: “Maka adalah al-hakir menjatuhkan midad [tinta] kepada kertas ini dengan tiga sebab: pertama-tama yang menunjukkan Wujud Wahdat itu dengan segala wujud kathra [banyak] ini, dan kedua menyatakan bijaksana orang kulit putih memerintah negeri itu, dan ketiga daripada tiada tertahani rindu akan sekalian yang dirindukan di dalam Pontianak itu” (HM: 2).
Mengetahui Abdullah bakal diutus oleh pemerintah Belanda ke negeri asing dan membaca bahwa dalam Hikayat Mareskalek itu, dia bermaksud membahas kebijaksanaan “orang kulit putih memerintah negeri”, maka timbul pertanyaan apakah karangan itu pesanan dari pemerintah juga. Namun, jawabannya tidak jelas, oleh karena mustahil kiranya pemerintah kolonial, yakni pada waktu itu Raffles, menyuruh seorang penulis mengagung-agungkan Daendels.
Menurut Chambert-Loir (2014: 84), lebih mungkin hikayat itu ditulis oleh Abdullah dan dipersembahkannya kepada Sultan Syarif Qasim serta adiknya Usman (yang akan menjadi sultan juga), dengan harapan memperoleh kedudukan di Pontianak. Andaikan demikian, bak jauh panggang dari api, harapan itu ternyata tak terkabul, dan Abdullah tetap tinggal di Jawa. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada 1818-1819, atas permintaan seorang pembesar Petapahan [sebuah kerajaan kecil di tepi Sungai Siak, beberapa jauh di hulu Pekanbaru] yang mengasingkan diri ke Jawa, Abdullah mengolah kembali buah pikirannya ihwal ilmu pemerintahan, serta beberapa kisah dan contoh yang diambil dari zaman Daendels untuk menulis sebuah karangan baru yang sama sekali lain daripada karangannya yang pertama, tetapi sama-sama dijuduli Hikayat Mareskalek dalam beberapa katalogus naskah dan uraian tentang sastra Melayu.
Judul itu sebenarnya dua kali meleset oleh sebab karya Abdullah itu, lebih-lebih yang kedua, lebih mirip kitab atau risalat tinimbang hikayat. Dalam karyanya yang pertama (Hikayat Mareskalek), Abdullah mengumpulkan sejumlah kisah perihal Daendels sebagai contoh kelihaian orang Eropa dalam ilmu pemerintahan.
Dalam karyanya yang kedua (yang kemudian diberikan nama baru dalam Zaini-Lajoubert, 2008, yaitu Arsy al-Muluk), Daendels hanya disebut beberapa kali saja di antara banyak sumber lain, sebagai bahan penguraian tentang kewajiban dan tugas seorang raja. Oleh karena itu, Arsy al-Muluk boleh dikatakan termasuk jenis karangan yang disebut fikih siasah dalam tradisi Arab dan yang dinamakan karya adab ketatanegaraan oleh Harun Jaelani dalam karyanya, Pemikiran Adab Ketatanegaraan Kesultanan Melayu (2003).
Sebagaimana kitab dan hikayat lain di Indonesia pada waktu itu, karya Abdullah tersebar dalam bentuk naskah dan disalin di berbagai tempat: versi Hikayat Mareskalek yang pertama disalin di Tanjung Pinang pada 1827 dan di Palembang empat tahun kemudian, sedangkan Arsy al-Mulk disalin di Pulau Penyengat pada 1882 dan 1886. Perhatian orang Belanda terhadap karya Abdullah cukup besar juga: kedua karya Abdullah itu diringkas dengan cerkas oleh van Ronkel pada 1918.
Selain itu, Abdullah menunjukkan pendidikan yang cukup tinggi dalam bidang agama. Karangan Arsy al-Muluk disusunnya seperti sebuah kitab, dengan mengutip pebagai sumber dalam bahasa Arab yang disertai terjemahan Melayu, dan yang selalu ditautkan dengan masa kontemporer. Kutipan-kutipan itu membuktikan pengetahuannya luas dan disusun sedemikian rupa dapat menyoroti beberapa gagasan secara jelas dan cerdik.
Karangannya tentang Siam dan Bali lain sekali susunannya. Abdullah menggunakan pelbagai dongeng setempat untuk merekonstruksikan sejarah, sehingga mencampurkan mitos dan fakta. Namun, bagian yang merupakan hasil pengamatannya sendiri, menunjukkan dia sebagai seorang pengamat yang pandai.
Arkian, melihat karangan-karangan Abdullah, kita dapat menarik sekadar simpulan. Abdullah al-Misri termasuk golongan pengarang Melayu, beserta Ahmad Rijaluddin, Abdullah Munsyi, dan Khatib Lukman, yang pada paruh pertama abad ke-19 tampil sebagai individu dan mengutarakan pendapatnya sendiri, bukan melanjutkan sebuah tradisi anonim.
Dia malah, seperti Ahmad Rijaluddin dan Abdullah Munsyi, menulis sebuah laporan perjalanan. Namun sebenarnya, Abdullah al-Misri tidak termasuk golongan generasi pengarang yang terpengaruh oleh pendidikan Eropa: dia tergolong suatu tradisi asing lain, bersama pengarang lama, seperti Nuruddin al-Raniri dan Bukhari al-Johori, yakni pengarang yang–atas pengaruh Islam (Arab dan Parsi)–yang meneroka jagat politik semasa dan menandai perubahan zaman.
Apabila mengecam raja-raja Nusantara karena naik takhta sebagai hak warisan, bila memuji teknologi administrasi Eropa (antara lain pendaftaran dan pencacahan segala jenis masyarakat dan hasil pertanian), pabila mengambil seorang asing dan kafir sebagai teladan, Abdullah menengarai krisis politik masanya, yakni awal zaman penjajahan.